Perubahan Bermula dari Ruang Kelas
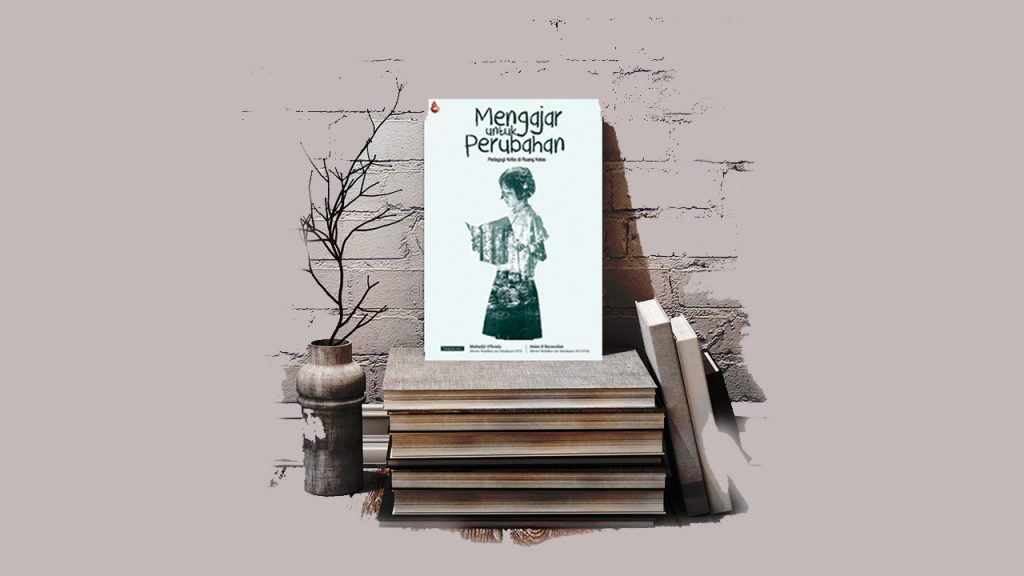
Oleh : Edi Subkhan*
Judul : Mengajar untuk Perubahan: Pedagogi Kritis di Ruang Kelas
Penulis : Bambang Wusido (Ed.)
Penerbit : Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur, bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Sekolah Tanpa Batas (STB)
Terbitan : pertama, November 2017
Ukuran : 14 cm x 21 cm; 152 halaman
ISBN : 978-602-6293-35-0
Kiranya tak ada hal lain yang harus dipentingkan oleh guru dalam mengajar di kelas selain siswa. Oleh karena itu, pembelajaran harus berangkat dari siswa. Mengenali masalah-masalah yang mereka alami, kemudian mengaitkan pembelajaran dengan dunia mereka. Dengan demikian, pembelajaran jangan didikte oleh desain kurikulum yang kaku. Jangan pula terpancang tuntutan menyelesaikan satu materi tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
Pesan itulah yang muncul dari buku “Mengajar untuk Perubahan: Pedagogi Kritis di Ruang Kelas” (2017). Buku setebal 152 halaman ini memuat cerita menarik dari praktik pembelajaran yang dilakukan oleh 9 (sembilan) guru di berbagai sekolah. Beragam kisah dituturkan secara naratif, hingga relatif renyah dibaca tanpa harus berkerut-kerut kening kita. Dari cerita guru mengajak siswa-siswinya belajar langsung di alam, menulis lagu, hingga simulasi demonstrasi, semuanya inspiratif.
Selama ini jika kita dengar keluhan para guru, termasuk dengan hadirnya Kurikulum 2013, adalah keharusan mereka mengikuti standar kaku dan target-target belajar yang sudah dipatok dalam jangka waktu tertentu. Pada akhirnya guru menjadi sekadar “tukang ngajar”, atau “operator kurikulum”. Belum menjadi pihak yang dapat menghidupkan kurikulum hingga pembelajarannya betul-betul bermakna (meaningful learning) bagi siswa.
Guru terjebak pada gaya pembelajaran konvensional yang terpaku pada ruang kelas dan buku teks resmi dari pemerintah. Improvisasi hampir tidak ada, karena takut akan menjauhkan pembelajaran dari mencapai tujuan pembelajaran yang sudah tertera di dokumen kurikulum resmi. Karena tidak dapat betul-betul menyentuh hati siswa, banyak masalah belajar justru menyalahkan siswa. Siswa nakal, tak mau sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), siswa selalu disalahkan.
Kisah pembelajaran di buku ini berbeda. Siswa selalu dilihat sebagai subjek yang harus dipahami keutuhan dirinya sebagai manusia. Kisah Diyar Ginanjar, guru di SD dan SMA Semesta Hati, Cimahi, misalnya, tak pernah melihat Ray, siswa pecandu game online, sebagai sumber masalah. Walau ia sendiri sempat dicaci-maki dan diludahi. Ginanjar justru empati pada Ray. Karena yakin perilaku kasar Ray bukan bawaan lahir, bukan pula masalah personal. Ada persoalan psiko-sosial yang menjadi sebabnya. Alhasil Ginanjar berhasil membujuk Ray agar mau bersekolah.
Hal serupa dituturkan Usep Saepul Husna, yang sempat mengajar 1 (satu) tahun di Raja Ampat, Papua Barat. Ia tak mau menuruti nasehat teman sesama guru di sekolahnya untuk menjauhi Haer, anak kepala suku setempat yang terkenal nakal. Bukan hanya karena ia tak pernah sopan pada guru, konon ia pernah menantang guru berkelahi hanya karena hal sepele. Haer, yang punya banyak pengikut, didekatinya pelan-pelan. Diajaknya nonton film di rumah dinas tempat Husna tinggal.
Akhirnya kenakalan Haer dapat ditaklukkan oleh Husna. Bukan dengan hukuman, bukan pula dengan iming-iming hadiah (reward), melainkan dengan ketulusan dan kasih sayang. Bayangkan jika anak-anak seperti Haer yang telanjur dicap nakal oleh guru-gurunya justru diabaikan. Atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Tentu ia akan makin menjadi-jadi. Walau sudah tidak mengajar di sekolahnya Haer, hubungan baik Husna dan Haer tetap terjalin hingga sekarang.
Hingga Husna mengungkapkan rasa harunya ketika ditelpon Haer, “Bapa, saya sudah kerja. Bapa mau pulsa kah…?” Dan Haer mengirimkan pulsa Rp. 100.000 kepada Husna yang biasanya mengisi pulsa hanya Rp. 10.000.
Kreativitas para guru dalam mengajar tersebut tentu tidak datang tiba-tiba. Adalah Sekolah Tanpa Batas (STB), sebuah komunitas pendidikan berperspektif pedagogi kritis yang telah menginisiasi penyelenggaraan pelatihan guru transformatif untuk mereka. Buku ini pun digagas agar publik tahu bahwa guru sudah seharusnya tak dikungkung oleh kurikulum. Mengacu pada gagasan pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire, Henry Giroux, dan kawan-kawan, STB mengajak para guru untuk terlebih dulu mengubah cara pandang mereka mengenai siswa dan pendidikan dalam arti luas.
Pedagogi kritis dirasa perlu dijadikan sebagia pegangan ideologis agar pembelajaran punya arah yang jelas hingga pada aksi nyata dan perubahan sosial (social changes/social transformation). Tidak sekadar menuntaskan materi yang dituntut oleh pemerintah di kurikulum dan buku-buku teksnya. Pedagogi kritis memandang bahwa praksis pendidikan harus kontekstual, yakni mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia kehidupan siswa-siswinya. Agar apa yang dipelajari disadari sebagai hal yang betul-betul bermakna dan berguna bagi mereka dan lingkungannya.
Belajar bukan sekadar untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, melainkan mengubah keadaan jadi lebih baik. Dalam perspektif pedagogi kritis, pendidikan dilihat selalu berkaitan dengan konteks sosio-kultural. Hal itulah yang mengarahkan agar jika terdapat masalah belajar dari siswa, perlu ditelusuri sebab psiko-sosio-kulturalnya. Bisa jadi ada masalah keluarga, lingkungan, dan lainnya. Masalah-masalah itulah yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum mengajak siswa untuk belajar materi-materi pelajaran.
Bisa jadi masalah tersebut akan turut diselesaikan seiring proses pembelajaran. Bisa juga diselesaikan di awal. Satu film bagus yang dapat menggambarkan perspektif ini adalah Freedom Writers (2007) yang dibintangi Hilary Swank. Kriminalitas dan rasisme yang melibatkan siswa-siswinya di kelas menjadi prioritas yang harus diselesaikan seiring mengajak mereka belajar bahasa Inggris.
Di tengah riuh rendah liputan mengenai rendahnya kualitas guru di Kompas beberapa waktu lalu, buku ini memberikan gambaran lain mengenai para guru berkualitas yang lebih menjanjikan.




